Tanah Bogor Rp3.000–Rp6.000 per Meter Persegi: LHKPN Mangihut Sinaga Dinilai Tak Masuk Akal, INDECH Desak Audit Khusus

Jakartra, MI - Nama Mangihut Sinaga kembali berada di pusat sorotan, kali ini bukan semata karena pusaran penyidikan korupsi LPEI, melainkan karena satu kejanggalan telanjang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya menjelang duduk di Senayan.
Puluhan bidang tanah di Kabupaten Bogor dicantumkan dengan nilai yang bukan sekadar murah, tetapi nyaris tidak masuk akal dalam konteks harga tanah Indonesia hari ini.
Dalam LHKPN tertanggal 14 Agustus 2024, Anggota Komisi III DPR RI yang berlatar belakang Jaksa itu melaporkan belasan bidang tanah di Bogor dengan luas total puluhan ribu meter persegi. Namun nilai yang dicantumkan membuat publik terperangah. Tanah seluas 2.601 m² hanya dilaporkan Rp14,95 juta.
Bidang 1.070 m² bernilai Rp6,15 juta. Tanah 6.312 m² dihargai Rp36,29 juta. Jika dirata-ratakan, nilainya berkisar Rp3.000–Rp6.000 per meter persegi.
Angka ini bukan sekadar di bawah harga pasar. Ini anomali ekstrem.
Sebagai pembanding, harga tanah di Bogor pada 2024–awal 2026, bahkan di wilayah non-prime sekalipun, berada pada kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah per meter persegi.
Di Bogor Barat, Dramaga, Ciomas, hingga Cijeruk, harga lazim berkisar Rp2–3 juta/m². Di Cibinong, Citeureup, dan Gunung Putri, harga rata-rata Rp2–5 juta/m². Kawasan yang disebut “murah” sekalipun tidak pernah menyentuh angka ribuan rupiah per meter.
Dengan logika paling konservatif—misalnya Rp500 ribu/m²—tanah seluas 2.600 m² seharusnya bernilai Rp1,3 miliar, bukan belasan juta rupiah. Selisihnya mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat. Ini bukan selisih tafsir, melainkan jurang realitas.
Kejanggalan ini makin mencolok karena jumlahnya bukan satu dua bidang, melainkan berulang dan sistematis. Ada pola yang konsisten: luas besar, nilai sangat kecil. Pola semacam ini lazim dikenal dalam praktik under-reporting aset, yakni pelaporan kekayaan dengan nilai jauh di bawah harga wajar untuk menekan total harta di atas kertas.
Masalahnya, LHKPN bukan catatan pribadi. Ia adalah instrumen publik untuk menguji integritas pejabat negara. Ketika seorang anggota DPR RI—yang juga mantan pejabat eselon I Kejaksaan Agung—melaporkan aset dengan nilai yang bertabrakan dengan logika pasar, publik berhak bertanya keras: ini kelalaian, manipulasi, atau pengaburan yang disengaja?
Pertanyaan ini tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas. Nama Mangihut Sinaga ikut mencuat dalam penyidikan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penyidik menemukan penguasaan mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan tersangka klaster LPEI, memunculkan dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan.
Meski Mangihut membantah mengetahui asal-usul aset tersebut, rangkaian fakta ini membentuk satu garis merah yang sulit diabaikan: aset besar, nilai kecil di atas dokumen.
Yang membuat perkara ini semakin problematik adalah latar belakang Mangihut sendiri. Ia menghabiskan lebih dari tiga dekade sebagai jaksa, menempati posisi strategis, memahami betul konsekuensi hukum dari laporan kekayaan yang tidak wajar. Sulit diterima akal jika kejanggalan sebesar ini dianggap sekadar “salah input” atau “penilaian lama”.
Dalam praktik administrasi negara, nilai LHKPN memang bisa menggunakan NJOP. Namun NJOP tanah di Bogor pun tidak pernah jatuh ke level Rp3.000 per meter persegi. Bahkan NJOP terendah di wilayah terpencil sekalipun masih ratusan ribu rupiah per meter. Artinya, alasan teknis semakin rapuh.
Publik kini dihadapkan pada paradoks telanjang: di satu sisi, negara menggembar-gemborkan transparansi dan perang melawan korupsi; di sisi lain, laporan kekayaan pejabat tinggi memuat angka yang secara matematis dan ekonomis tak dapat dipertanggungjawabkan.
Jika kejanggalan ini dibiarkan berlalu tanpa klarifikasi dan pemeriksaan serius, maka LHKPN akan berubah menjadi formalitas kosong—sekadar daftar angka yang tidak mencerminkan realitas. Lebih jauh lagi, pembiaran semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk: bahwa menyusutkan nilai aset di atas kertas adalah praktik yang bisa ditoleransi.
Tanah di Bogor jelas bukan tanah fiktif. Yang kini dipertanyakan publik adalah kejujuran nilai yang melekat padanya. Dalam iklim krisis kepercayaan terhadap elite politik, perkara “tanah Rp3.000 per meter” ala Mangihut Sinaga bukan isu kecil.
Ia adalah simbol tentang seberapa serius negara menjaga akal sehat, etika, dan transparansi pejabat publik.
Perlu audit khusus
Setelah publik dibuat terperangah oleh nilai puluhan bidang tanah di Kabupaten Bogor yang dilaporkan hanya ribuan rupiah per meter persegi, kritik keras datang dari kelompok pemantau integritas pejabat publik.
Sekretaris Jenderal Indonesian Ekatalog Watch (INDECH), Order Gultom, menilai laporan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai kesalahan administratif biasa. Menurutnya, perbedaan antara nilai yang dilaporkan dan harga pasar sudah terlalu ekstrem untuk ditoleransi akal sehat.
“Kalau selisihnya hanya 10 atau 20 persen, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi ini selisihnya ratusan kali lipat. Tanah di Bogor dilaporkan Rp3.000 sampai Rp6.000 per meter persegi. Itu bukan undervalue lagi, itu menihilkan nilai aset,” kata Order kepada Monitorindonesia.com, Senin (26/1/2026).
Order menegaskan, Bogor bukan wilayah terpencil tanpa akses. Bahkan di kawasan pinggiran sekalipun, harga tanah sudah lama berada di kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah per meter persegi. Karena itu, ia menilai nilai tanah versi LHKPN Mangihut mustahil dijelaskan dengan dalih NJOP rendah atau harga lama.
“NJOP Bogor tidak pernah serendah itu. Bahkan tanah sawah atau kebun di lokasi paling pinggir pun tidak pernah dihargai ribuan rupiah per meter. Jadi alasan teknis apa pun sulit diterima,” ujarnya.
INDECH melihat adanya indikasi pengaburan kekayaan yang berbahaya jika dibiarkan. Menurut Order, LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat utama publik untuk mengawasi potensi konflik kepentingan dan akumulasi kekayaan tidak wajar pejabat negara.
“Kalau LHKPN bisa diisi dengan angka yang jelas-jelas bertentangan dengan realitas pasar, lalu dianggap sah, maka sistem pengawasan kekayaan pejabat runtuh. Ini preseden buruk,” tegasnya.
Order juga menyoroti konteks politik dan hukum yang menyertai nama Mangihut Sinaga. Sebagai anggota Komisi III DPR RI dan mantan pejabat eselon I Kejaksaan Agung, Mangihut justru seharusnya menjadi contoh kepatuhan dan transparansi.
“Beliau ini bukan orang awam hukum. Puluhan tahun di kejaksaan, paham betul soal konsekuensi laporan palsu atau tidak wajar. Maka publik wajar curiga: apakah ini sekadar salah input, atau memang disengaja untuk mengecilkan total kekayaan?” kata Order.
INDECH secara terbuka mendesak pemeriksaan dan klarifikasi menyeluruh oleh lembaga berwenang, termasuk penelusuran ulang nilai aset tanah di Bogor tersebut. Jika perlu, kata Order, dilakukan audit khusus dan pemanggilan untuk memastikan kebenaran laporan.
“Ini bukan soal menyerang pribadi. Ini soal menjaga akal sehat publik dan kredibilitas sistem. Kalau kasus seperti ini dibiarkan, pesan yang sampai ke masyarakat adalah: laporan kekayaan pejabat boleh fiktif selama rapi di atas kertas,” ujarnya.
Dengan kritik keras dari masyarakat sipil dan sorotan publik yang kian tajam, kasus “tanah Bogor Rp3.000 per meter” tak lagi sekadar anomali angka. Ia berubah menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi pejabat negara, sekaligus ujian bagi negara: berani membongkar kejanggalan elite, atau membiarkannya larut sebagai angka mati dalam dokumen LHKPN.
Topik:
Mangihut Sinaga LHKPN Tanah Bogor Harta Kekayaan Pejabat Dugaan Pengaburan Aset Transparansi Pejabat INDECH Order Gultom Integritas DPR Isu KorupsiBerita Selanjutnya
KPK Ulik Eks Stafsus Menag Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Berita Terkait
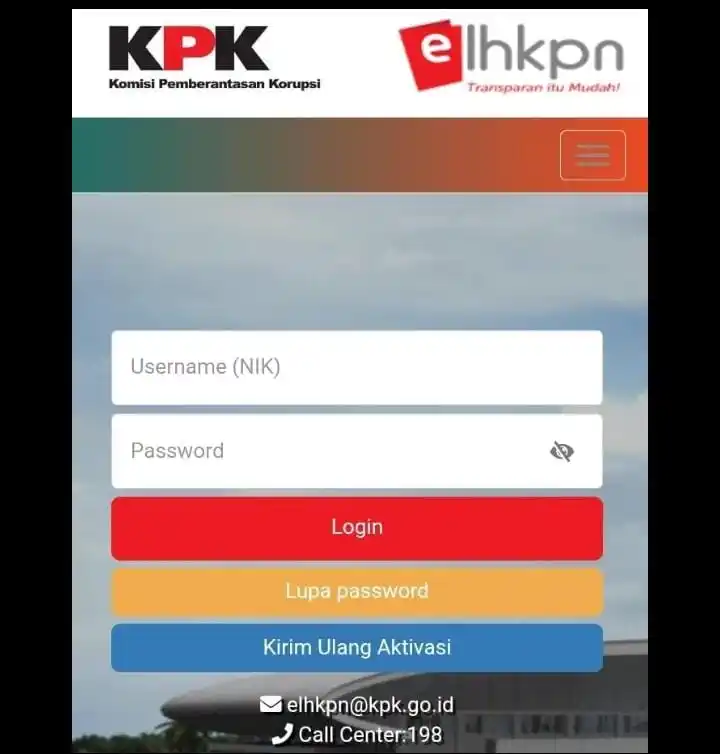
Kepatuhan LHKPN 2025 Masih Rendah, KPK Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor
20 jam yang lalu

Baru 35,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta, KPK: Transparansi Masih Sekadar Slogan
3 Februari 2026 04:44 WIB

Pakar Desak PPATK Usut Harta Mangihut, Nama Terseret Bayang-Bayang Skandal LPEI Rp 1,8 T
28 Januari 2026 16:44 WIB

Mangihut Sinaga Tegaskan Tak Terlibat Kasus LPEI Rp 1,8 T: Hormati Proses Hukum, Jangan Bangun Opini Liar
28 Januari 2026 12:50 WIB



